Iboe
Ia peluk tubuh dingin itu sangat erat. Sembari menangis, Anna Marie Jarvis masih belum bisa menerima kepergian ibunya. Sampai pipinya basah, air matanya berurai disertai isak yang dalam. Anna tak percaya ibunya benar-benar telah tiada.
Namun apalah daya, Anna bukan Nabi Isa, utusan Tuhan yang dikaruniai mukjizat bisa mehidupkan orang mati. Ia hanya manusia biasa yang mencintai ibunya. Cinta yang tak pernah ia bagi dengan lelaki manapun, kecuali Ayah dan Tuhannya.
Sebelum ibunya meninggal, Anna teringat pada suatu hari, di taman kawasan Philadelphia, ia mengajak ibunya yang sakit jantung itu menghirup udara segar pagi musim semi. Dengan suara lirih dan napas sengal, ibunya berpesan pada Anna, “kelak ketika aku tiada, aku berharap manusia menghargai pelayanan tanpa batas yang diberikan ibu mereka. Dan Negara memperingati hari ibu sebagai sebuah memorial, karena seorang ibu berhak atas itu.”
Pesan itu terekam jelas. Anna kembali menatap wajah ibunya yang layu, sekujur tubuhnya yang kaku. Ia pegang erat-erat tangan ibunya lalu kemudian berjanji di dalam hati, “harapanmu harus dibayar tuntas.” Ann Reeves Jarvis (baca: Ibu Anna Marie Jarvis) meninggal pada 9 Mei 1905.
Tiga tahun setelah kematian ibunya, tahun 1908, Anna mengadakan peringatan untuk menghormati ibunya dan semua kaum ibu di Gereja Episcopal Methodist Andrews, Grafton, West Virginia. Sebelum seluruh negara bagian di Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur pada tahun 1911. Lalu diresmikan oleh Woodrow Wilson dengan menandatangi Deklarasi Hari Ibu sebagai hari libur nasional yang jatuh pada hari minggu kedua bulan Mei.
Hari Ibu yang digagas Anna Marie Jarvis semakin populer. Meski di sebagian besar dunia, Hari Ibu dirayakan dengan cara, hari, dan tanggal yang berbeda. Ia merasa sedikit lega, cita-cita ibunya telah tertunaikan.
Tapi sore itu, ditengah senja tertutup salju, Anna merasa ganjal. Hari Ibu yang masyhur itu ia anggap gagal karena dijadikan ‘tambang mas’ sebagian korporat. Baginya Hari Ibu telah kehilangan makna akibat dilindas mesin konsumerisme buatan tangan kaum kapitalis.
Anna tak ingin Hari Ibu sekejadar jadi tren, yang dilakukan tapi tak membekas. Karena menurutnya kasih sayang seorang ibu tak sebanding dengan pembelian dan pemeberian bunga, permen, dan kartu ucapan. Ia mengutuk keras formalitas itu, meski tak seluruhnya menyalahkan. Ia ingin lebih, Hari Ibu harus sakral.
Bersama asosiasi the Mother Day Internasional Association, Anna berusaha mengembalikan makna asli Hari Ibu. Hari yang sepatutnya dijadikan momentum untuk menghargai jasa seorang ibu bagi keluarganya; anak dan suaminya ataupun lingkungan sosialnya. Ia mengajak kita tenggelam dalam lautan kasih sayang ibu yang tanpa parih dan tak lekang. Dengan sadar sepenuhnya, bukan sebutuhnya.
Dalam buku Memorirializing Motherhood: Anna Jarvis and the Defense of Her Mother’s Day, sejarawan Katharine Antilini dari West Virginia Wesleyan College menyitir perkataan Anna soal kasih sayang ibu yang ia lambangkan seperti White Dianthus Caryophyllus:
“Warna putihnya adalah untuk melambangkan kebenaran, kemurnian dan kasih sayang yang luas dari cinta ibu; aroma, ingatannya, dan do’anya. Anyelir tidak menjatuhkan kelopkanya, tetapi memeluk mereka sampai ke jantung ketika mati, dan demikian juga, ibu-ibu memeluk anak-anak mereka ke hati mereka, cinta ibu mereka tidak pernah mati. Ketika saya memilih bunga ini, saya teringat tempat tidur ibu saya yang berwarna merah muda.”
Usaha ulet Anna untuk mereformasi Hari Ibu terus berlanjut sampai tahun 1940an. Pada tahun 1948 ia meninggal di usia 84 tahun di Philadelphia’s Marshall Square Sanitarium. Ia tak meninggalakan apa-apa. Ia tak pernah jadi seorang ibu bagi anaknya, kecuali memantaskan diri jadi anak untuk ibunya. Anna Marie Jarvis bukan seorang ibu, ia lebih dari itu, yaitu Ibu dari Hari Ibu (The Mother of Mother’s Day).
Kurang lebih dua dekade sebelum Anna Marie Javis meninggal, di belahan dunia lainnya; Nusantara hidup seorang Djami. Perempuan keturunan Pribumi totok yang nyaris tak ada dalam catatan sejarah, selain sebagai salah satu aktifis organisasi Darmo Laksmi.
Djami bingung, kenapa takdir lahir sebagai perempuan dianggap inferior. Padahal ia tak pernah minta dilahirkan sebagai perempuan. Namun ia yakin sepenuh iman, Tuhan menciptakan perempuan tak untuk direndahkan. Baginya, lelaki atau siapapun yang mencela kodrat perempuan, sama juga menistakan kuasa Tuhan.
Ingatan itu masih terasa segar. Pada masa Djami kecil, perempuan bukan hanya direndahkan oleh Kolonial Belanda dengan membatasi partisipasi perempuan dalam domain publik. Namun masyarakat Pribumi pun demikian, stigma perempuan begitu mengakar. Djami paham betul, ia tak bisa merubah sejarah masa lalu. Namun ibarat kapal, sejarah bisa berganti arah haluan. Djami punya harapan, percaya masa depan.
Maka dalam Deklarasi Perempuan Indonesia di Yogyakarta tahun 1928, Djami berpidato dengan judul “Iboe”. Dalam pidatonya ia melampiaskan sesuatu yang tertahan; menuntut keadilan gender. Meminta kesamaan hak termasuk dalam ranah pendidikan. Agar definisi perempuan tidak sebatas urusan sumur, kasur, dan dapur.
Akses pendidikan bagi perempuan menurut Djami sangat penting. Sebab perempuan adalah calon ibu, yaitu madrasah pertama bagi anaknya. “Tak ada seorangpun akan termasyhur kepandaian dan pengetahuannya kalau bukan karena ibu atau istrinya yang tinggi juga pengetahuan dan budinya,” kata Djami dalam pidatonya di depan peserta Kongres..
Membaca kembali pidato Djami adalah mengikuti alur cerita yang alot, penuh sarkastik, dan lugas. Campur aduk antara kepedihan atas ke-peremupuan-nya dan optimisme yang memuncak. Waktu itu bicara status perempuan dan ibu masih tabu. Namun ia menyusun teks itu dengan semangat perubahan paradigma berpikir dan rasionalitas pemikiran yang memadai.
Kesedihan saya membacanya lagi pidato Djami bukan karena atas segala kisah pilu seorang Djami. Tapi karena pidato Djami adalah puncak dari gunung es di permukaan air laut. Ada yang lebih makro dari Djami, yakni pengebirian perempuan secara sosial tanpa mengingat jasa-jasa mereka (baca: perempuan), lebih-lebih seorang ibu.
Dalam penutup pidatonya sekali lagi ia tegaskan bagaiaman seorang perempuan harus mendapat kelas sosial dan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Karena bagaimanapun kata Djami, dalam buku Lady Emilly Lutyans yang ia kutip: Ibu akan mengajarkan anaknya sejak dalam kandungan. Pidato Djami usai.
Sedasawarsa kemudian, pada Kongres Perempuan Indonesia III. Peserta Kongres menyepakati tangal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Mereka turut andil pula dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perbaikan keadaan perempuan Indonesia. Misalnya perbaikan gizi ibu dan anak balita, menghentikan pernikahan dini, apalagi perdagangan perempuan dan anak.
Indonesia pun telah merdeka. Mereka terus mengambil peran dalam pembangunan negara. Maka pada tanggal 22 Desember 1953, dalam peringatan Kongres Perempuan Indonesia yang ke-25, Presiden Soekarno mentapkan setiap tanggal 22 Desember diperingati Hari Ibu, melalui Dekrit Presiden RI No. 316 Tahun 1953.
Mungkin dua kisah di atas sedikit cukup menggambarkan sejarah lahir Hari Ibu. Tinggal bagaimana kita, khusunya saya pribadi, dapat menangkap pesan tersirat dari peringatan ini. Tentu bukan sekedar membuat ucapan “Selamat Hari Ibu” yang mewarnai media sosial, melainkan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas jasa dan kasih sayang tanpa pamrih mereka.
Dalam Islam, setidaknya ada dua pendapat yang berbeda ketika memandang perayaan Hari Ibu. Diskursus kajian hukum ini memang sudah dibahas oleh sejumlah pakar. Antara lain ulama Al-Ahzar Mesir, sedikitnya ada empat ulama yang mengatakan Hari Ibu haram di lakukan oleh umat Islam. Sebut saja misalkan Syekh Mutawalli as-Sya’rawi dan Syehk Ali Mahfudh serta sejumlah cendekiawan seperti Musthafa al-Adawi dan Abdul Hamid Kisyk.
Mereka beranggapan bahwa dalam syariat Islam tradisi demikian tak pernah ada. Lebih pada itu dalam pandangan mereka, mengapa perayaan ini tidak dibolehkan karena taklid buta terhadap tradisi Barat. Barat menciptakan peringatan ini sebagai bentuk hipokrit. Perayaan demikian merupakan instrumen menebus abai yang sudah mereka lakukan akibat terlalu materialistik. Kendati demikian, para ulama tersebut tak memvonis kafir bagi Muslim yang melakukan perayaan dimaksud.
Di sisi lain, Syehk Yusuf al-Qaradhawi menilai peringatan Hari Ibu bukan termasuk perkara yang haram karena syariat tidak melarang. Meski ia sendiri tak terlalu tertarik untuk melakukan perayaan tersebut. Asal menurutnya jangan sampai disamakan dengan menggunakan istilah I’d (hari raya) yang korelasinya sangat dekat dengan agama.
Beliau menambahkan, jangan sampai perayaan ini malah menyinggung perasaan anak yatim piatu. Jika beliau harus memilih antara merayakan Hari Ibu dengan memperhatikan nasib dan kondisi anak yatim piatu, beliau cenderung pada pilihan yang kedua. Meski beliau mengakui dengan perayaan ini dapat membahagiaka ibu, namun dalam Islam kewajiban membahagiakan ibu tak dibatasi waktu, sesuai prinsip Surat Luqman Ayat 14.
Terlepas dari itu semua, sudahkah kita berbuat baik pada orang tua, terutama ibu kita? Atau malah terjebak pada tren dan formalitas belaka? Anda sekalian lebih tau menjawabnya.
Sepekan yang lalu, pada tanggal 13 Desember lalu, salah satu media massa mengabarkan pembunuhan. Kabar mirisnya adalah orang tua yang dibunuh anak kandungnya. Sebelum ibunya dibunuh, anak bengal itu menyeret ibunya yang kemudian berakhir dibacok dengan golok. Perempuan setengah baya itu meregang nyawa. Anak itu jadi durhaka.
Saya tidak mengatakan anak jaman now lupa suatu tempat yang kata Zawawi Imron dalam puisi Ibunya ‘gua pertapaan yang kasih sayangnya seluas samudera’. Biarlah sabda Nabi Muhammad membuktikan bahwa salah satu tanda akhir zaman ialah ketika ibu melahirkan majikannya.
Selamat Hari Ibu…
Penulis : Rahmat Hidayat (santri aktif di Pondok Pesantren Nurul Jadid)



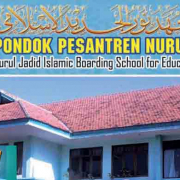








Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!