Pilpres dan Fenomena Post Truth
Di tengah maraknya berita-berita hoax, diperparah lagi dengan makin leluasanya setiap pengguna media sosial (Medsos) mengupload, mengolah, menggoreng, mempublikasikan informasi seenaknya sendiri seolah-seolah makin membuat kabur mana kebenaran dan mana kebohongan. Kebenaran dan kebohongan seperti menjadi satu, membaur saling menerima sekaligus menegasi, menolak sebagian sekaligus menerima bagian yang lain. Bahkan yang lebih ekstrim, sebuah kebohongan dibalik seolah sebuah kebenaran, dan diterima sebagai kebenaran, sementara kebenaran tenggelam dianggap sebuah kebohongan. Setiap orang memiliki kuasa untuk mengatur kebenarannya sendiri sehingga apa yang diinformasikan di tengah-tengah publik diyakini sebuah kebenaran. Persoalannya kemudian bagaimana kebenaran dan kebohongan bekerja di tengah-tengah publik sehingga ia menguasai setiap orang. Konsumen informasi medsos seakan tidak perlu lagi menelusuri dan mengidentifikasi lebih jauh kebenaran atau kebohongan yang sesungguhnya?.
Era Pasca Kebenaran
Menurut teori korespondensi, kebenaran dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dan berkorespondensi dengan kenyataan (reality). Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap sebuah kebohongan. Artinya kebenaran merupakan sebuah realita, ia bukan anggapan, opini, isu dan bukan pula wacana. Ia adalah kenyataan sejarah, bukan impian dan bukan pula masa depan. Ia memiliki landasan empirik, sebuah perjalanan masa lalu yang berangkat dari fakta-fakta emperis. Oleh karenanya kebenaran dapat diukur, diuji, diverifikasi karena sifatnya objekif. Sebaliknya jika sesuatunya tidak memiliki landasan empirik, hanya berupa informasi-informasi liar yang tidak mempunyai sejarah, maka ia dapat dipahami sebagai kebohongan. Keduanya, kebenaran dan kebohongan, belakangan saling menguat dan mengklaim dirinya sebagai kebenaran.
Ajang pilkada, pilgub, pilpres dan pil-pil yang lain menemukan momentumnya untuk bertarung di tengah semrawutnya kebenaran dan kebohongan. Masing-masing Pasangan Calon (Paslon) mendapatkan angin segar untuk membuat kebenarannya masing-masing. Antara satu dengan yang lain saling mengklaim sebagai yang benar. Serang-menyerang, mencemooh, membuli, bahkan mengakfirkan antar Paslon menjadi sebuah pemandangan dan suguhan sehari-sehari. Masyarakat pun semakin bingung mana sebenarnya informasi yang benar dan yang bohong tentang masing-masing Paslon. Di tengah sulitnya membedakan keduaya (kebenaran dan kebohongan), pada akhirnya “kebenaran semu” dalam menjadi sebuah proyek. Artinya setiap paslon berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan masyarakat meyakini apa yang diinformasikan dan apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran. Akhirnya citra positif di depan publik menjadi proyek utama untuk mempengaruhi dan menyakinkan publik bahwa ia sebagai yang benar, yang lain adalah salah. Sekalipun kerja-kerja pencitraan juga merupakan kebohongan yang dibungkus seolah sebagai kebenaran.
Dalam momentum seperti ini fakta senyatanya tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding dengan emosi dan keyakinan personal, itulah yang disebut fenomena post truth. Sebuah era pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing sedemikian rupa dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus bersaing dengan media sosial yang semakin mengaburkan antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non fiksi.
Oleh karenanya, yang diperebutkan oleh Paslon adalah hati masyarakat dengan pendekatan yang bersifat primordial-emosional dari pada pendekatan yang rasional. Sehingga menjadi wajar kemudian jika penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai instrumen politik yang paling ampuh untuk menjual serta meningkatkan elektabilitas Paslon tertentu. Sebab isu tersebut sangat dekat dengan emosi setiap orang dan sangat sensistif karena bersentuhan langsung dengan personal seseorang. Sehingga isu SARA tetap menjadi alat politik yang paling seksi yang dapat memancing hati calon pemilih. Lihat saja misalnya sejak terjadinya Pilpres 2014 hingga sekarang isu yang paling seksi dan trend adalah isu yang berkaitan dengan SARA.
Maka dari itu, penggunaan media sosial dirasa memiliki efektif untuk menggerakkan, mengarahkan seseorang pada pilihan Paslon tertentu. Makanya tidak heran jika Medsos menjadi makhluk baru yang paling berkuasa belakangan. Kebebasan menyampaikan opini, informasi dan berita dan sebagainya satu sisi bernilai positif untuk mengawal kekuasaan dan proses demokrasi, tapi pada sisi lain sangat merusak dan mengganggu stabilitas kekuasaan. Berangkat dari hal itu, Jurgen Habermas, Filsuf Jerman, pernah mengatakan bahwa konektifitas media sosial (Medsos) akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Medsos bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global serta menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Sebaliknya medsos juga bisa menjadi ancaman bagi tegaknya demokrasi dan pluralisme.
Di Rusia misalnya, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukhraina, Perancis dan Jerman. Bahkan kemenangan Donal Trump disinyalir karena kampanye hitam lewat medsos. Termasuk kemenangan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang disinyalir membuat keyboard army untuk menyebarluaskan narasi palsu dan lain sebagainya. Pada posisi ini, orang tidak lagi melihat kebenaran dengan mengonfirmasi fakta, tapi lebih dipengaruhi opini yang berkembang. Pada akhirnya siapa yang mampu memerankan dan mengendalikan opini publik ia akan menjadi penguasa bahkan menentukan kebenaran. kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta-fakta, melainkan ditentukan oleh siapa media sosial digerakkan dan dikuasai. Ujungnya masyarakat akan tersegmentasi pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kecendrungan dan kedekatan emosionalnya. Kedekatan emosional biasanya ditentukan oleh hal-hal primordial seperti paham keagamaan atau agama, golongan, daerah, ras dan suku bangsa. Dengan demikian ancaman berikutnya adalah pluralsime. Yakni, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat tidak lagi dipelihara dan dijaga sebagai kekayaan dengan membangun toleransi dan kesalingpengertian tapi dibikin ektrim agar saling memisah dan berhadap-hadapan hanya untuk merebut suara masyarakat. Atara satu golongan dibenturkan dengan golongan yang lain, dengan memperuncing perbedaan dari pada mencari persamaan.
Pada level ini, informasi yang diolah dan dikemas sedemikan rupa lambat laun mengikis kesadaran dan daya kritis masyarakat. Opini publik yang menguasai masyarakat apakah berupa kebenaran atau sebaliknya kebohongan, penipuan maupun fiktif dengan tanpa sadar diterima dan dipercaya sebagai kebenaran. Hilangnya kesadaran dan daya kritis inilah sebagai penanda keberhasilan medsos yang menyebarkan berita propaganda dalam mengontrol pikiran bahkan kesadaran seseorang. Inilah era post truth, sebuah fase pasca kebenaran.
Penulis: Ainul Yakin, Dosen UNUJA, Pegiat di Community of Critical Sosial Research (Commics) Probolinggo.

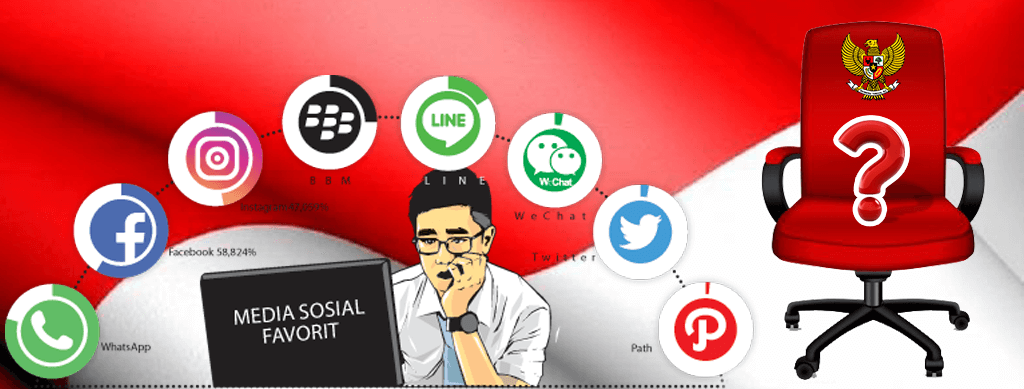










Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!