Eksistensi Pendidikan Pesantren
Semenjak pelantikan presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintahan Indonesia untuk kedua kalinya, kita dapat melihat isu radikalisme, terorisme dan intolerasi menjadi perhatian khusus di periode kali ini. Hal ini ditegaskan dengan terpilihnya Fachrul Razi sebagai menteri Agama (tanpa melihat latar belakang), yang dianggap dapat menjadi ikon kuat untuk memukul mundur problem-problem di atas. Bukan main, di awal tugasnya menteri Agama mulai menunjukkan aksinya dengan pelarangan cadar dan celana cingkrang dalam instansi pemerintahan yang dianggapnya memiliki paham radikal.
Penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme. Tidak sampai di situ, Menag mengatakan sebagian besar pelajar di Indonesia mendukung aksi radikalisme berbasis agama, beliau mengutip survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip), yang menyatakan 52 persen pelajar setuju aksi radikalisme. Yang mungkin seiring perjalanan waktu angka-angka tersebut terus bertambah. Rakyat Indonesia sepatutnya khawatir melihat hasil penelitian tersebut mengingat potensinya masih berlanjut. Namun, bukan berarti menjadi sebuah ‘kecemasan sosial’, saya katakan demikian selama tidak menghasilkan perbuatan destruktif dan masih dalam koridor aman. Tapi apakah penelitian tersebut dapat mereprentasikan “kelemahan” pendidikan di Indonesia?
Pergerakan islamisme-jihadisme
Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dibilang variatif dari berbagai persepektif dan tidak terlalu rumit, akan tapi mencukupkan hasil survei sebagai nilai akhir dirasa kurang valid mengingat pergerakan radikalisme juga mengalami kesulitan di berbagai sektor pendidikan. Mungkin benar, saat ini pendidikan di Indonesia sangat rentan terjangkit radikalisme, kita dapat menyaksikan aksi islamisme-jihadisme yang banyak diikuti oleh pelajar dari berbagai starata, mereka telah terbius oleh “rayuan surgawi” yang termuat komersial Agama.
Pergerakan Islamisme-jihadisme terbilang sangat mengkhawatirkan, bukan sekedar pemahaman yang mengandung “morfin” yang memabukkan, melainkan pula karena prioritas konsumennya adalah kaum muda. Saya melihat kaum muda saat ini sedang mengalami pubertas beragama, yang sering melakukan aksi frontal dan terlalu fanatik dalam kepercayaannya yang mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan dan pembaharuan berfikir. Mengenai hal ini, Grand syaikh Azhar prof. Ahmad at-Tayyib di dalam pembukaan konferensi internasional Tajdid al-Fikr wa al-Ulum al-Islamiyyah menyampaikan “sebab stagnasi ranah ijtihad dan gerakan pembaharuan di era modern ini, diakibatkan keengganan kuam muda dan umat Islam untuk mengemban tanggung jawab, dan membiarkan fanatisme beragama baik di dalam bidang pendidikan atau pendakwahan”. Islamisme-jihadisme juga acap kali membenturkan berbagai struktur sosial, budaya, tradisi, dengan dalil-dalil Agama, alih-alih untuk memuluskan tujuan yang terselubung dibalik itu semua.
Perputaran islamisme-jihadisme ini juga belum ditemukan buntutnya, meskipun setiap tahunnya jumlah pelajar yang mendukung islamisme-jihadisme bertambah, namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tolerasi umat Islam Indonesia. Saya beranggapan itu semua terjadi, selama pertahanan pendidikan Pesantren tetap terjaga yang telah menemani berdirinya Negara ini.
Peran Pendidikan Pesantren dalam Toleransi
Saya memaksudkan pesantren di sini adalah pesantren dengan orientasi ideologi Ahlussunnah wal jamaah, jelas bukan pesantren Wahabiyah atau sering juga di sebut pesantren Salafi. Pendidikan pesantren tradisional (salaf) telah membuktikan perannya dalam membentuk generasi yang dibekali pemahaman beragama yang benar dan toleran. Saya juga beranggapan pendidikan pesantren menjadi satu-satunya institusi yang belum terpapar radikalisme. Hal ini dikarenakan pendidikan Pesantren tetap menjaga ke-aslian turats ulama salaf, melestarikan tradisi sanad yang jelas, dan bukan hanya sebatas teoritis melainkan praksis yang terus diajarkan oleh para Kiai.
Pendidikan pesantren juga berupaya melakukan pembaharuan seiring perubahan zaman, kita lihat beberapa pesantren sudah mulai mengembangkan berbagai fan keilmuan, tidak lagi berkutat pada kitab klasik (yang pada umumnya berwarna kuning, sehingga disebut kitab kuning). Namun, dari semua kemapanan pendidikan pesantran ini, saya melihat stagnasi didalamnya karena para santri hanya dituntut mengaji dan mengesampingkan mengkaji. Mungkin hal ini yang mengakibatkan santri sulit mengeksploitasi pengetahuannya di dalam teori atau ide yang lebih segar.
Ketahanan pesantren dalam menghadapi islamisme-jihadisme tidak mungkin bertahan lama kecuali adanya faktor pelindung. Di dalam tulisannya Prof. Azyumardi Azra bahwa ketahanan pesanteran dipengaruhi oleh beberapa faktor pelindung yaitu kiai, kitab kuning, tradisi pendidikan berorientasi kemasyaraktan, relasi baik dan workable dengan ormas Islam, tradisi akomodasi dan penerimaan perbedaan dan keragaman berbagai bidang. Saya juga menambahkan faktor pelindung lainnya adalah solidaritas santri dan kesadaran bermasyarakat meminjam dauh almarhum kiai Zaini Mun’im “ Orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan rakyat banyak”. Wallahu A’lam.(*)
*Penulis Zainal Fanini adalah alumni santri PP. Nurul Jadid Asrama Diniyah lulusan MA Nurul Jadid angkatan 17 dan saat ini masih menempuh Pendidikan strata 1 di Universitas Al Azhar Mesir.
Editor : Ponirin


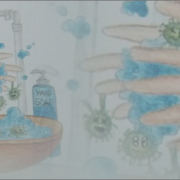







Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!